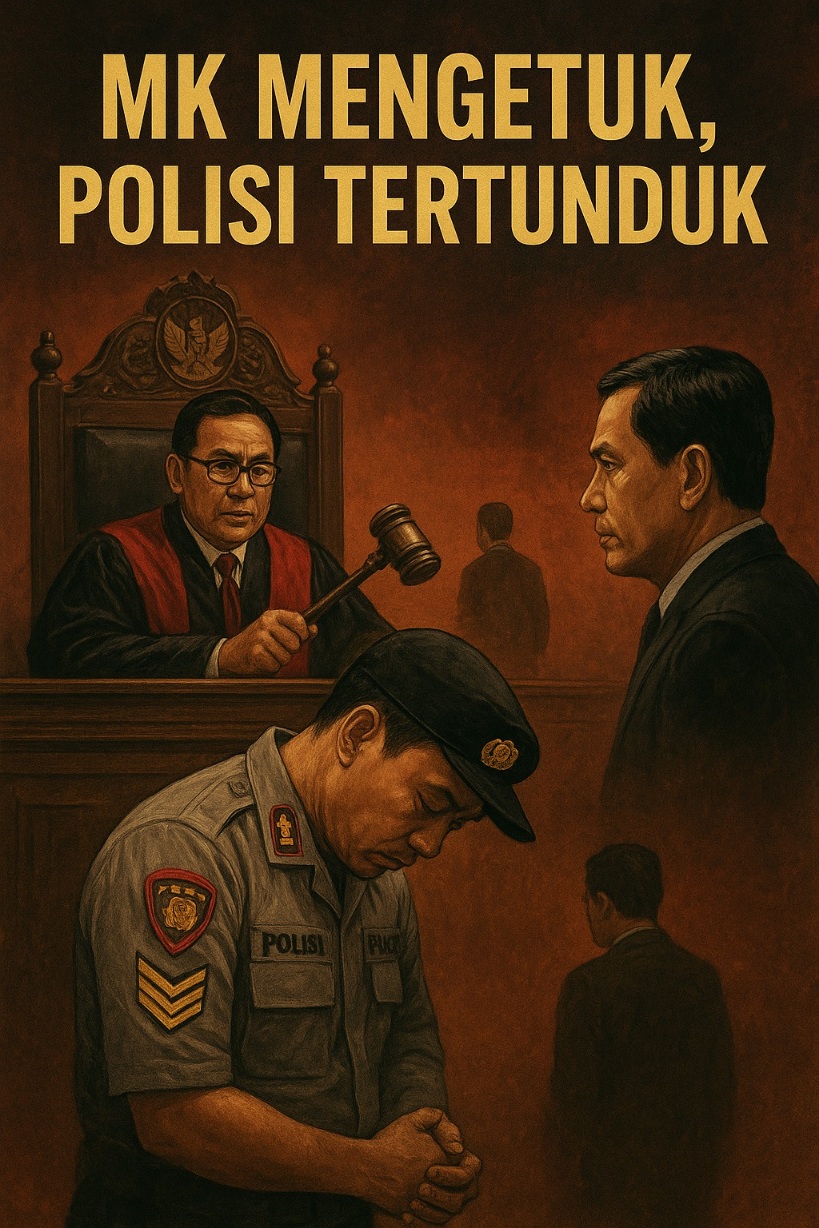Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Apa yang sesungguhnya diharapkan masyarakat dari pegawai sektor publik atau pemerintahan? Jika ditanyakan secara umum, hampir semua orang akan menjawab sama, yaitu masyarakat menginginkan layanan terbaik dari negara.
Harapan ini wajar mengingat masyarakat merupakan pembayar pajak yang berkontribusi terhadap keberlangsungan negara. Oleh karena itu, bukan hal yang salah jika mereka menginginkan layanan yang diberikan pemerintah cepat, ringkas, tanpa prosedur yang berbelit-belit.
Namun akan menjadi lebih menarik untuk dicermati ketika pertanyaan tersebut sedikit dimodifikasi menjadi apakah layanan terbaik harus identik dengan aparat pemerintah yang selalu sibuk, bekerja tanpa henti, bahkan hingga lembur? Pada titik yang seringkali terjadi bias.
Perspektif di sektor nonpemerintahan dipakai untuk mengukur kinerja pada sektor pemerintah sehingga faktor kesibukan menjadi indikator tunggal. Birokrat hanya diukur dengan standar seberapa sibuk pegawai bersangkutan. Jika terlihat lengang, langsung dicap tidak produktif, padahal logika kerja pemerintahan tidak sesederhana itu.
Untuk memahami persoalan ini, kita perlu terlebih dahulu membedakan cara kerja sektor pemerintah dan sektor nonpemerintah. Secara garis besar, dunia kerja dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu sektor pemerintahan dan sektor di luar pemerintahan.
Sektor nonpemerintah (baik yang berorientasi profit seperti perusahaan maupun non-profit misalnya yayasan) pada dasarnya bergerak dengan logika aliran uang. Profit atau surplus finansial menjadi ukuran utama keberhasilan organisasi.
Maka setiap aktivitas pegawai di sektor ini akan selalu dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap target finansial. Waktu luang di tengah jam kerja dipandang sebagai pemborosan (idle capacity) yang berpotensi menggerus keuntungan.
Jika suatu aktivitas tidak mendukung pencapaian profit atau justru menambah beban biaya, organisasi biasanya akan melakukan efisiensi. Praktik umum efisiensi yang dilakukan dapat berupa memangkas kegiatan tersebut, mengalihdayakan pekerjaan, atau mengurangi jumlah pegawai. Dalam sektor nonpemerintahan amat wajar jika setiap pegawai dituntut untuk selalu berkontribusi dan meminimalkan adanya waktu luang.
Berbeda halnya yang terjadi pada sektor pemerintahan di mana profit atau surplus bukan menjadi tujuan utama. Sebagian besar unit pemerintah tidak memiliki tugas memungut pendapatan, hanya sedikit institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan alokasi belanja pun sudah ditetapkan sepenuhnya dalam dokumen anggaran yang disetujui oleh pemerintah dan perwakilan masyarakat.
Sehingga ruang gerak pada sebagian besar institusi pemerintah terbatas pada pengelolaan belanja yang pagunya sudah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan belanja yang diamanatkan tersebut memiliki tujuan berupa pemberian layanan kepada masyarakat serta pemenuhan hak-hak warga.
Atas pertimbangan tersebut maka indikator kinerja (KPI) yang paling relevan bagi birokrasi bukanlah profit atau surplus finansial namun lebih kepada indikator berupa ketepatan waktu layanan, kualitas pelayanan, serta persentase capaian layanan kepada masyarakat. KPI berbasis keuntungan pendapatan atau minimalisasi biaya tidak selalu cocok diterapkan, karena tidak semua unit pemerintah mengelola uang yang dapat dipadankan dengan badan usaha.
Perbedaan mendasar inilah yang tampak seolah-olah terdapat unit pemerintah yang "menganggur" pada jam kerja tertentu. Dari sudut pandang masyarakat awam, hal ini sering dianggap pemborosan. Namun ada beberapa alasan rasional mengapa kondisi tersebut bisa terjadi.
Pertama berkaitan dengan keterbatasan anggaran operasional. Sebagus apa pun ide pelayanan publik, realisasinya tetap bergantung pada ketersediaan dana. Banyak pegawai sebenarnya memiliki ide kreatif tetapi tidak bisa bertindak tanpa ketersediaan pendanaan.
Misalnya bagi unit yang bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan mungkin sudah mengetahui titik-titik kerusakan, tetapi tidak dapat melakukan perbaikan sebelum ada alokasi anggaran untuk pemeliharaan. Dalam situasi seperti ini akan tampak pegawai yang seolah-olah menganggur, padahal kendalanya yang dihadapi lebih bersifat struktural bukan karena faktor kemalasan.
Alasan kedua berkaitan dengan jenis layanan pemerintah yang memang dirancang untuk kondisi siaga alias preventif. Contoh paling jelas adalah pemadam kebakaran. Secara filosofis keberadaan petugas pemadam kebakaran sebagai langkah pencegahan sebelum bencana terjadi alias untuk berjaga-jaga.
Jikalau kemudian mereka memiliki banyak waktu luang justru pertanda baik dikarenakan jumlah kasus kebakaran yang rendah. Waktu luang mereka bukan tanda kelalaian, melainkan cerminan keberhasilan fungsi preventif. Logika yang sama berlaku pada banyak layanan darurat lainnya.
Argumen ketiga berkaitan dengan modernisasi dan digitalisasi layanan yang berdampak terhadap cara kerja birokrasi. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan integrasi basis data antarunit, mempercepat proses, dan memangkas prosedur yang dulu berbelit-belit.
Banyak layanan yang sebelumnya memerlukan tatap muka berjam-jam kini bisa diselesaikan secara daring dalam hitungan menit. Dampaknya tentu kebutuhan pegawai berkurang sedangkan layanan yang diberikan menjadi lebih optimal karena proses yang efisien.
Sayangnya keberhasilan modernisasi layanan sering disalahpahami oleh banyak pihak. Alih-alih mengakui bahwa teknologi telah meningkatkan produktivitas, yang terjadi malah muncul dorongan untuk menambah tugas-tugas baru hanya agar pegawai "terlihat sibuk".
Padahal penambahan tugas yang tidak selaras dengan tugas utama berisiko mengaburkan tujuan organisasi. Lebih jauh lagi hal tersebut bisa memicu tumpang tindih kewenangan antarunit karena setiap instansi berlomba mencari "pekerjaan" agar tidak dicap menganggur.
Selain adanya tambahan tugas baru, sejumlah aturan untuk mendokumentasikan setiap aktivitas bagai "solusi" demi mengesankan seolah-olah sibuk. Masalahnya tambahan kegiatan berupa pencatatan segala aktivitas harian justru memicu pola pemborosan gaya baru akibat penyediaan perangkat untuk keperluan dokumentasi.
Sisi negatif lainnya malah semakin memperpanjang meja layanan demi mengejar target pengisian aktivitas harian. Sebuah layanan yang seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu satu jam misalnya terpaksa diulur hingga berhari-hari agar dapat dipakai untuk mengisi logbook harian pegawai. Kondisi ini yang berpotensi menjadi pemicu rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Meski layanan semakin terdigitalisasi, keberadaan aparat pemerintah tetap tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Banyak tugas pelayanan publik harus terus tersedia terlepas dari faktor kalkulasi untung dan rugi. Negara harus hadir secara nyata di tengah masyarakat, baik melalui pelayanan, pengawasan, maupun perlindungan.
Selain itu, keberadaan aparat negara juga memiliki makna simbolik dan politis yang penting yakni sebagai bukti nyata eksistensi negara di suatu wilayah. Dalam sejarah sengketa Pulau Miangas, kemenangan Belanda atas klaim Spanyol salah satunya ditentukan oleh fakta bahwa Belanda secara terus-menerus menempatkan aparat pemerintah di pulau tersebut.
Artinya kehadiran aparat pemerintahlah yang kemudian menjadi penentu klaim suatu negara terhadap sebuah wilayah. Ketiadaan aparat pemerintah apalagi jika telah sepenuhnya tergantikan oleh komputer bisa jadi menyulitkan penentuan klaim suatu wilayah jika terjadi sengketa.
Terlepas dari topik "menganggur", tentu saja kritik terhadap birokrasi tetap diperlukan. Tidak bisa dimungkiri bahwa masih ada pegawai yang kurang disiplin, inefisien, termasuk prosedur layanan yang berbelit. Solusi atas persoalan tersebut bukanlah memaksa semua pegawai harus terlihat sibuk, melainkan memperbaiki sistem, menyederhanakan regulasi, dan memperjelas standar pelayanan publik.
Analoginya sederhana misalnya kita tidak menilai kualitas rumah sakit dari seberapa sibuk dokternya, tetapi dari seberapa responsif tenaga kesehatan dalam melayani pasiennya. Begitu juga kita tidak menilai sekolah dari banyaknya tugas guru, tetapi seberapa baik seorang guru mampu mentransfer ilmu ke para murid.
Dengan logika yang sama tentu saja untuk mengukur kinerja pemerintah seharusnya dinilai dari kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan dari tingkat kesibukan para pegawainya.
Idealnya kita menginginkan birokrasi yang ramping, profesional, dan berorientasi pelayanan. Jumlah pegawai harus proporsional dalam artian tidak berlebihan, tetapi juga tidak dipangkas secara sembrono hingga merusak kualitas layanan. Aparat pemerintah tidak harus selalu terlihat sibuk, tetapi harus selalu siap dan sigap dalam memberikan layanan.
Pada akhirnya, perbedaan perspektif antara sektor pemerintah dan nonpemerintah memang akan terus menjadi bahan diskusi. Namun jika kita memahami perbedaan filosofis antar keduanya, harapan masyarakat dapat ditempatkan pada posisi yang lebih realistis. Pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama dengan jumlah aparatur yang cukup, profesional, serta fokus pada tugas utamanya.
Menambah beban tugas hanya demi menciptakan kesan sibuk bukanlah solusi. Alih-alih meningkatkan kinerja, langkah tersebut justru berpotensi mengaburkan mandat utama negara dan membuat pelayanan publik terbengkalai. Tingkat ukuran keberhasilan institusi pemerintahan bukanlah seberapa sibuk pegawainya, melainkan seberapa baik mereka dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
(miq/miq)

 2 hours ago
4
2 hours ago
4